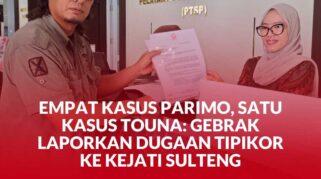Kasus ini kini menjadi cermin dari persoalan yang lebih mendasar, yakni rapuhnya tata kelola pemerintahan dan lemahnya integritas birokrasi di tingkat daerah.
Pada awalnya, publik hanya mengetahui bahwa terdapat 16 titik usulan WPR yang disebut secara resmi oleh Bupati. Namun, fakta di lapangan menunjukkan inkonsistensi yang mengkhawatirkan.
Dalam dokumen resmi yang ditandatangani langsung oleh Bupati, jumlah titik WPR melonjak menjadi 53. Lonjakan data yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang menambah titik tersebut, atas dasar apa, dan bagaimana mungkin kepala daerah menandatangani dokumen strategis tanpa memahami isinya secara menyeluruh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik, tetapi refleksi atas ketidakteraturan dalam sistem administrasi pemerintahan.
Jika benar kepala daerah tidak mengetahui isi dokumen yang ia tandatangani, maka hal itu menunjukkan dua kemungkinan: kelalaian yang serius dalam fungsi pengawasan, atau adanya intervensi dari pihak-pihak yang memanfaatkan celah birokrasi demi kepentingan tertentu.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal merupakan prinsip utama. Namun, situasi di Parigi Moutong memperlihatkan sebaliknya.
Ketika publik menanti klarifikasi yang solutif, yang muncul justru pernyataan yang saling bertentangan, saling menyalahkan, dan memperkeruh suasana. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antarpejabat serta minimnya kendali komunikasi politik yang efektif di tingkat pemerintahan daerah.
Sebagai kepala daerah, Bupati semestinya berperan sebagai figur yang mampu menenangkan situasi, bukan menjadi bagian dari polemik itu sendiri.
Kepemimpinan yang baik menuntut kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara substansial, bukan dengan membangun narasi defensif di ruang publik.
Jika memang terjadi kesalahan prosedural atau manipulasi internal, penyelesaiannya harus dilakukan secara profesional, tertutup, dan bermartabat — bukan melalui saling tuding di hadapan media.
Semakin sering pejabat publik berbicara tanpa arah yang jelas, semakin nyata pula lemahnya kendali birokrasi di bawah kepemimpinan tersebut.
Retaknya koordinasi ini, jika tidak segera diatasi, akan menggerus dua hal paling berharga dalam pemerintahan: kredibilitas dan kepercayaan rakyat.
Kasus 53 titik WPR seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan, bukan dijadikan panggung pembelaan diri atau ajang pencitraan politik.
Kepemimpinan sejati tidak diukur dari seberapa keras seseorang menolak tudingan, melainkan dari sejauh mana ia mampu menuntaskan kekacauan yang terjadi di bawah tanggung jawabnya.
Jika situasi ini terus berlarut sementara kepala daerah masih sibuk membangun narasi di media, publik memiliki hak untuk mempertanyakan arah kepemimpinan yang sedang berjalan. Sebab pada akhirnya, pemerintahan bukanlah panggung untuk menunjukkan siapa yang benar atau salah, melainkan ruang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan benar, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Dan bila sampai hari ini persoalan mendasar seperti WPR saja tidak mampu diselesaikan dengan tuntas, maka pertanyaan publik menjadi sangat relevan: apakah Kabupaten Parigi Moutong masih benar-benar dipimpin, atau hanya sedang dipertontonkan?
Penulis : Faradiba Zaenong
(Ketua KADIN Kabupaten Parigi Moutong)