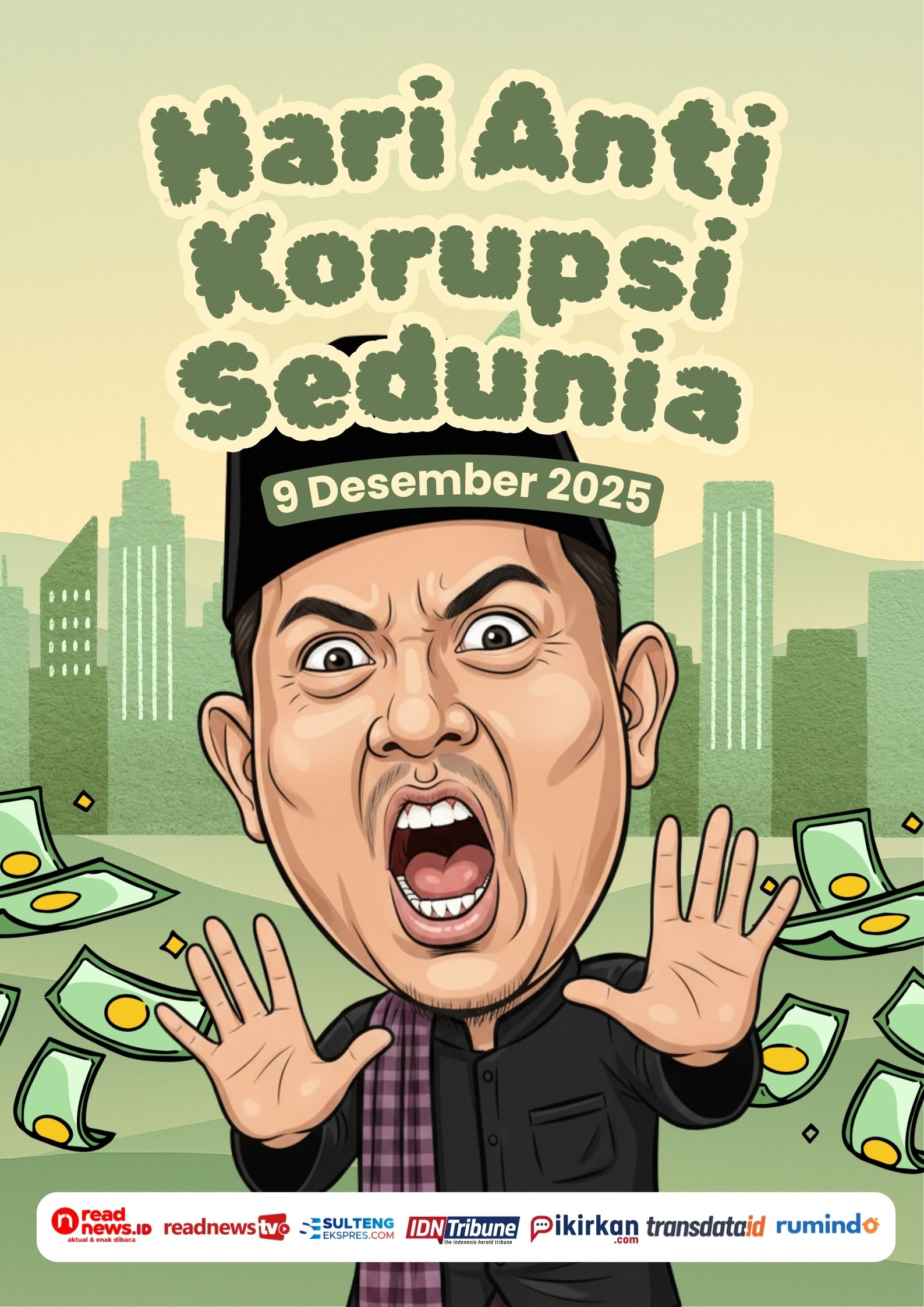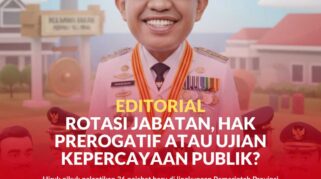Salah satu contoh konkret adalah kondisi petani kelapa. Di banyak desa pesisir dan dataran rendah, petani masih menjual hasil panen dalam bentuk kelapa bulat atau kupas babi—produk mentah dengan nilai ekonomi sangat rendah. Padahal, semua bagian kelapa—air, daging, sabut, tempurung hingga batok—memiliki nilai jual tinggi jika diolah secara modern. Solusi ke depan adalah membangun ekosistem industri kelapa yang terintegrasi, mulai dari pengolahan minyak VCO, serat sabut (coco fiber), media tanam (cocopeat), karbon aktif, hingga furnitur batok. Dengan sistem ini, nilai tambah akan tinggal di desa, bukan sekadar lewat tengkulak.
Di sisi fiskal, ketimpangan juga tampak dalam struktur penerimaan negara. Menurut laporan BPK 2023, dari total setoran pajak dan retribusi industri nikel yang mencapai ratusan triliun rupiah, hanya sekitar 2% yang masuk ke kas daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Ini artinya, sebagian besar manfaat fiskal dinikmati pemerintah pusat, sementara beban sosial, lingkungan, dan infrastruktur ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan fiskal, dan memperkuat tuntutan agar mekanisme bagi hasil disesuaikan dengan dampak nyata di lapangan.
Meski demikian, ada peluang besar yang bisa ditangkap. Industri turunan nikel saat ini berkembang pesat. Tidak hanya menghasilkan feronikel dan stainless steel, kini Morowali menjadi lokasi pembangunan pabrik precursor dan cathode—komponen penting baterai kendaraan listrik. Ini membuka jalan bagi Indonesia, melalui Sulawesi Tengah, untuk naik kelas menjadi produsen bernilai tambah dalam rantai pasok global industri energi bersih.
Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada sektor ekstraktif seperti tambang tetap menyimpan risiko. Fluktuasi harga nikel di pasar global sangat tinggi, dan perubahan teknologi baterai dapat menggeser permintaan material. Karena itu, penting bagi Sulawesi Tengah untuk segera melakukan diversifikasi ekonomi. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, kelautan, serta industri hilir berbasis komoditas lokal seperti kelapa harus menjadi prioritas jangka panjang. Terlebih, data menunjukkan bahwa sektor pertanian menyerap lebih dari 40% tenaga kerja di Sulawesi Tengah (BPS, 2024), namun kontribusinya terhadap PDRB hanya sekitar 15,8%—tanda ketimpangan struktural yang harus segera dijembatani.
Tantangan lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia lokal. Banyak industri masih merekrut tenaga kerja luar daerah karena kurangnya tenaga terampil. Diperlukan strategi besar dalam pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan industri, dan link-and-match antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Pemerintah daerah juga perlu mendorong keterlibatan warga lokal dalam struktur kepemilikan industri melalui koperasi, BUMDes, atau skema investasi kolektif yang memberi manfaat ekonomi langsung.
Jika potensi-potensi ini dikelola dengan visi yang tepat dan keberpihakan pada rakyat, maka Sulawesi Tengah tidak hanya akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga simbol dari transformasi ekonomi yang berkeadilan. Provinsi ini bisa menjadi bukti bahwa dari pinggiran Indonesia, bisa lahir simpul baru rantai pasok global yang inklusif dan berkelanjutan-dimana pertumbuhan tidak hanya dihitung dari angka, tetapi dari manfaat yang nyata bagi setiap warganya.
Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dari rantai pasok global. Namun peluang ini tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan keadilan distribusi manfaat. Ke depan, strategi pembangunan harus menjawab tiga tantangan utama: memperkuat SDM lokal, mempercepat hilirisasi dan integrasi industri, serta memastikan keberpihakan kebijakan pusat terhadap pembangunan daerah. Bila ini dilakukan secara konsisten, bukan tidak mungkin Sulawesi Tengah akan menjadi episentrum ekonomi baru di kawasan timur Indonesia, bahkan Asia Tenggara.
Oleh: Dr. Ir. Ihksan Syarifuddin, ST., M.M
Praktisi Marketing, Direktur Transdata Sulawesi Gemilang – Wakil Ketua Kadin Kota Palu